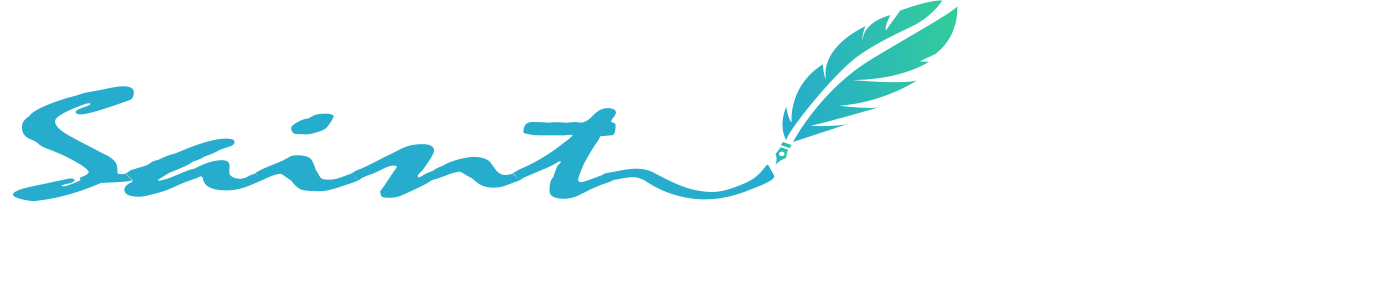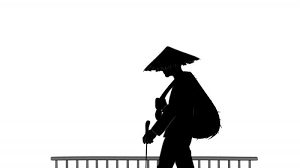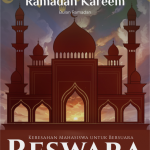Tersapu angin, dua lembar koran bekas itu akhirnya jadi sasaran empuk untuk alas tidurku malam ini. Dingin, mengitari seluruh trotoar jalan, emperan toko, dan segala jalan malam yang telah menjadi tempat istirahat termewah untuk manusia-manusia macam aku. Deru suara sedan mewah, truck gandeng, dan kendaraan-kendaraan pemakan jalan yang lain, sudah mulai bisa dihitung dengan jari. Beberapa lentera berlistrik sinar surya pun mulai meredup satu demi satu. Tapi tidak dengan aku, warga negara Indonesia dengan jabatan pemulung. Bergandeng dengan dua partner terbaik dalam pekerjaanku, jono dan anto. Meski udara kian mengigilkan seluruh elemen tubuh kami yang kian keronta, itu tidak cukup menjadikan alasan untuk kami terlelap. Seperti biasa, hasil mulung hari ini harus tetap terjaga. Jika tidak, ada saja cerita terbitnya fajar bersama raibnya penghasilan. Jika tidak, ada saja aparat keamanan atau penguasa wilayah menendang kami dari tempat istirahat ternyaman. Kejar-kejaran dan adu mulut, ya itu adalah makanan yang cukup mengenyangkan, untukku dan dua partner terbaikku.
“Bagaimana cara dapat uang satu juta ya?” celetuk anto, melerai sepi diantara kami bertiga.
“Mana cukup jon buat beli rumah? Paling-paling buat ngontrak, gak nyampek satu tahun,” sahut jono, sembari merebahkan tubuhnya dengan alas selembar kardus bekas air mineral.
“Mungkin 6 bulan, atau lebih. Dengan syarat kita puasa, hahaha” timpaku.
Pertanyaan jono, memang selalu mengarah kedepan. Diantara kami bertiga, memang dia yang paling cerdas. Jono mantan mahasiswa hukum, semester 3 berhenti kuliah karna ayahnya terjerat kasus korupsi. Memilih menjalani hidup dijalan, kemudian bertemu dengan aku dan anto. Manusia yang menjadikan jalan sebagai rumah untuk pulang.
“He ngawur-ngawur. Bukan gitu, kalian belum dapat kabar ya. Ada pasal RUU KUHP, yang kontrovesional,” jawab anto
“Duhh mahasiswa mulai lagi mulai lagi, mulai membicarakan politik. Basi dah basi, apapun yang terjadi di negeri ini, tidak ada ngaruhnya sama kita,” balas jono, menggerutu.
Aku hanya terdiam, memikirkan hubungan antara pasal RUU KUHP yang sama sekali tidak aku pahami, dengan uang senilai satu juta.
“Kamu ini jon, asal nyeletuk aja kayak janji manis tikus-tikus berdasi” balasku, sembari memukul kepala jono.
Kami bertiga pun hanyut dalam tawa.
“Emang ada apa to? Ayo cerita. Bukakan pintu hatiku dan jono, yang sudah enggan memikirkan negeri ngawur ini, hahaha” tanyaku pada anto.
Sambil merapikan alas tidurnya, anto menjawab pertanyaanku “Sekarang sudah gak ngawur, tapi ngawur bin hancur, parah sudah.”
“Gimana-gimana? Meski hanya gelandangan gini, aku sebenarnya juga peduli sama negara. Peduli sama pemerintah” jono beranjak dari tempat tidurnya.
“Peduli apa kamu ini? Peduli untuk menghujat pemerintah? Ya kan?” timpaku.
“Ha…. Ha…. Ha….,” lagi-lagi selalu ada selingan tawa, disetiap obrolan kami.
“Begini wahai partner kerjaku yang tak pernah bertopeng,” lanjut anto yang kemudian membenarkan posisi duduknya.
“Aku tadi bertemu dengan kawanku semasa kuliah. Banyak mahasiswa yang mau demo, ya itu karna pasal RUU KUHP yang nyeleneh” jelas anto.
“Wuuuh, keren kali negeri ini” sahut jono
“Jadi, ini ada hubungannya dengan kita” lanjut anto
Aku mulai menyerngitkan dahi, “apa yang salah dari kita? Tak pernah kita ngusik pemerintahan dan negeri ini” tanyaku, tak terima.
“Begini, dari penjelasan kawanku tadi, banyak pasal-pasal yang kontroversial. Nah, salah satunya pasal 432, yang intinya bahwa gelandangan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dapat denda Rp. 1 juta”
“Gilak, siapa yang buat pasal macam gitu? Ora gennah (tidak jelas)” jono mulai naik tikam.
“Ya gak tahu, aku hanya orang kecil. Tanpa anto, kita ini buta politik” balasku.
“Sebenarnya, kita ini bukan geledangan. Pemulung, bukan penjahat dan pencuri uang rakyat. Tikus trotoar yang lebih mulia, dari tikus-tikus berdasi” balas anto.
Memang benar, meski tampang kami gelandangan, kami lebih suka menamai pekerjaan ini Tikus Trotoar yang lebih Mulia. Apa lagi anto, mungkin karna kasus ayahnya itu, ia sangat benci dengan pemerintah yang makan uang rakyat, termasuk ayahnya sendiri.
“Terus pie ngene ki, mangan mbendino ae angel, kok bayari pemerintah 1 juta? (terus bagaimana ini, makan setiap hari saja sulit, kok mau bayari pemerintah 1 juta),” celetuk jono yang kebingungan.
Ya, karena aku dan jono lebih peduli dengan makanan untuk besok, daripada ulah-ulah pemerintah. Pasti, bingung dihadapkan masalah ini.
“Betul jon. Bagaimana nasib kita? Kaum tertindas,” balasku
“Bagaimana lagi. Ya dengan do’a, semoga aksi tetap damai, tanpa ditunggangi pihak-pihak tertentu. Negara kita semakin adil Makmur, pemerintah tetap jadi wakil rakyat yang mewakili hati rakyat,” tambah anto.
Aku dan jono hanya terdiam. Dalam situasi semacam ini, kami yang buta pendidikan dan birokrasi negara, hanya manggut-manggut mendengarkan pernyataan Anto. Barangkali, pernyataan semua orang.
“Kita ini bukan gelandangan, aku yakin kita lebih mulai dari pemerintah yang sewena-wena. Jadi jangan takut,” anto meneruskan pernyataannya.
Hening malam, hanya ada sayup plastik-plastik terbawa angin. Suasana masih sama, namun gejolak batin tak bisa dibohongi. Sebuta-butanya kami akan negara, jika ada peraturan nyelewang, menindas orang lemah, kami juga tidak terima. Tidak ada yang salah dengan pemulung, karena itu lebih mulia dibanding dengan konglemerat dari uang rakyat. (CAN)